Melihat Agama Lebih Jauh: Penyakit Keagamaan Masyarakat Urban
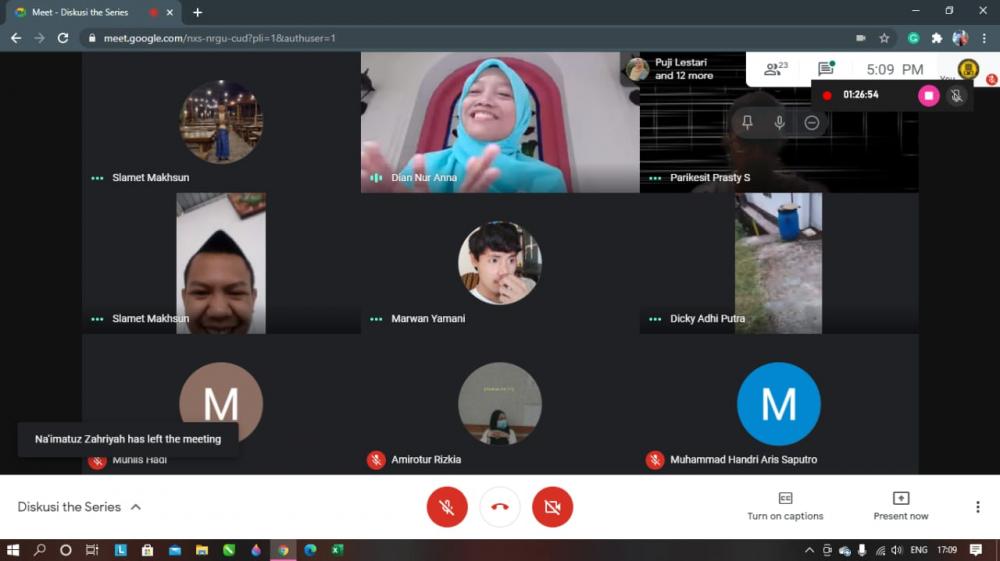
Melihat Agama Lebih Jauh: Penyakit Keagamaan Masyarakat Urban*
(Notulensi Diskusi Series #1 HMPS Studi Agama-Agama, Jum’at 12 Maret 2021, Narasumber Dr. Dian Nur Anna. )
Menurut Paul B. Horton, masyarakat diartikan sebagai kumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup berdampingan, tinggal dalam wilayah tertentu, serta memiliki kebudayaan yang bercorak sama, serta terjadi interaksi diantara anggotanya. Soerjono Soekamto menambahkan, bisa dikatakan masyarakat jika jumlahnya minimal dua orang. Dalam dinamikanya, suatu masyarakat tidak selalu mulus dalam artian pasti ada suatu problem yang menghinggapi, sehingga menghalangi laju menuju masyarakat yang aman dan sejahtera. Terlebih masyarakat kota, yang notabenanya sangat heterogen.
Di zaman kiwari, masyarakat perkotaan lazim disebut masyarakat urban. Istilah itu, berkenaan dengan gambaran suatu peradaban yang kurang lebih, ada empat ciri khasnya. Yakni tingkat literasi internet atau digitalisasi yang tinggi, mudah menyebarnya budaya baru (pop), masyarakat yang individualistik, serta memiliki mobilitas yang tinggi bila berhadapan dengan hal-hal yang baru. Namun, dengan perkembangan yang pesat itu, justru semakin banyak pula ‘penyakit’ yang dialami oleh masyarakat urban, entah dalam bidang politik, hukum, budaya, sosial, atau lainnya. Dan parahnya lagi, agama yang notabenenya sebagai ‘penyembuh kewarasan’ turut dimanfaatkan untuk suatu kepentingan tertentu. Inilah yang kemudian menjadi muasal patologi (penyakit) masyarakat. Terlebih, Indonesia ini, terbilang negara yang ‘religius’. Bila suatu isu agama disinggung, maka akan mudah kebakaran jenggot.
Di antara contoh patologi keagamaan seperti pemanfaatan dalil secara laterlek demi kepuasan nafsunya. Alih-alih mencari makna yang hakiki, malahan menggunakannya untuk memanipulasi. Inilah yang terjadi seperti dalam kasus poligami. Memang sebenarnya Nabi SAW pun membolehkannya. Tetapi, dengan beberapa syarat yang harus terpenuhi. Nah, karena syarat-syarat ini ada dalam keterangan yang dijelaskan ulama dan tidak rinci disebutkan dalam Al-Quran, oleh sebagian kelompok ‘pemuja’ poligami, tidak diambil. Karena bagi mereka, AL-Quran saja sudahlah cukup. Beh, sungguh parah. Padahal, banyak ayat-ayat Al-Quran yang membutuhkan pengkajian yang mendalam. Hasilnya, para perempuan menjadi korban nafsu birahi kelompok ‘pemuja’ poligami tersebut.
Atau contoh lainnya, seperti agama yang dijadikan ladang untuk mencari suara dalam pemilu, maraknya kriminalisasi yang mengatasnamakan agama, atau penipuan yang berkedok agama seperti biro umrah dan haji. Hal itu semua, memang akrab terjadi di masyarakat kota. Apa sebabnya? Yakni kurangnya literasi agama yang dimiliki. Seperti yang dialami umat Islam, rata-rata yang tinggal di perkotaan, saat kecil tidak memiliki waktu untuk belajar agama yang mendalam, karena memang ekosistem masyarakatnya yang kurang mendukung. Berbeda dengan masyarakat desa, sedari kecil sampai dewasa, kenyang dijejali ilmu agama. Hal ini bisa dibuktikan dengan menjamurnya pondok pesantren dan madrasah diniyah di desa-desa.
Untuk menjawab permasalahan demikian, maka key word-nya cuma satu. Perdalam ilmu agama. Perdalam literasi agamanya. Hal ini bisa dilakukan dengan cara memilih guru yang benar cum belajar pada ahlinya. Entah dengan cara mendatangi pusat-pusat kajian agama, atau agamawan itu sendiri yang membuat konten semisal Youtube yang sekiranya menarik dan bisa menjangkau masyarakat luas, apalagi sekarang eranya dunia maya. Setelah ajaran agama diserap dengan benar, maka hal itu secara otomatis akan membentuk output pemeluk agama yang, kata Gus Mus— saleh sosial dan saleh ritual. Demikianlah jika masyarakat telah mencapai dan atau memiliki budaya seperti, maka dengan sendirinya patologi yang menghinggapinya akan hengkang.
*Materi Pemaparan dari Ketua Kaprodi Studi Agama-Agama Dr. Dian Nur Anna
